Monopoli Terselubung di Balik Kebijakan Energi
Kehabisan stok di SPBU swasta seperti BP dan Shell bukan semata masalah logistik, melainkan akibat kebijakan yang mewajibkan impor bahan bakar melalui Pertamina. Aturan ini membuat swasta kehilangan kemandirian, menurunkan kualitas produk, dan menaikkan harga. Di baliknya, kebijakan tersebut didorong untuk menjaga kinerja BUMN, namun efeknya menciptakan monopoli terselubung yang menghambat kompetisi dan mengancam iklim investasi. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan ini agar kinerja BUMN tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan pasar dan semangat ekonomi terbuka.

Kehabisan stok bahan bakar di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan Vivo beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan besar, mengapa semua pemain swasta serentak menghadapi kendala pasokan? Jawabannya mengarah pada satu hal, kebijakan yang mengharuskan mereka mengimpor bahan bakar melalui Pertamina.
Kebijakan ini tampak sederhana, namun efeknya sangat serius. Dengan kewajiban membeli atau mengimpor lewat Pertamina, SPBU swasta kehilangan kemandirian bisnis. Mereka dipaksa mengikuti standar dan rantai pasok BUMN yang mendominasi pasar. Padahal, Pertamina dan SPBU swasta memiliki spesifikasi produk berbeda. Misalnya, bahan bakar Pertamina mengandung campuran etanol sekitar 3,5%, masih di bawah ambang batas 20% yang diizinkan pemerintah, tetapi berbeda dengan standar yang digunakan Shell atau BP yang tidak mencampurkan etanol sama sekali.
Konsumen yang terbiasa dengan kualitas bahan bakar murni tentu merasakan perbedaan performa kendaraan. Karena pasokan harus melalui Pertamina, SPBU swasta tidak hanya kehilangan kualitas produknya, tetapi juga terpaksa menjual dengan harga lebih tinggi akibat rantai distribusi yang tidak efisien. Akibatnya, sebagian SPBU swasta memilih mem-PHK karyawan, menyesuaikan operasional untuk dapat bertahan, dan meninggalkan ruang kosong dalam pasar bahan bakar nasional.
Ironisnya, hal ini terjadi di saat pemerintah mengklaim tingkat pengangguran berada di level terendah sejak reformasi. Kebijakan yang tampak administratif ini justru memberi dampak sosial-ekonomi langsung, bertolak belakang dengan narasi keberhasilan ekonomi nasional.
Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan ini tak lepas dari tekanan untuk menjaga kinerja BUMN. Sejak pembentukan Danantara, lembaga pengelola investasi BUMN, pemerintah menargetkan peningkatan dividen dari perusahaan pelat merah. Untuk mencapai target tersebut, BUMN “didukung” dengan berbagai regulasi yang disadari atau tidak mempersempit ruang gerak kompetitor swasta.
Hasilnya adalah bentuk monopoli terselubung, yakni semua aturan tampak legal, tetapi esensinya mematikan kompetisi. Tidak ada pasal yang dilanggar, karena aturan itu dibuat oleh pihak yang diuntungkan. Kondisi seperti ini menciptakan kesan bahwa berbisnis di Indonesia tidak lagi berpijak pada prinsip fair competition. Jika pola seperti ini berlanjut dan meluas ke sektor lain, dampaknya bisa serius. Investor asing akan ragu menanamkan modal, pelaku bisnis lokal kehilangan insentif untuk berinovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang diidamkan menjadi sulit tercapai.
Setiap kebijakan tentu memiliki konsekuensi. Meningkatkan kinerja BUMN adalah tujuan yang baik, tetapi jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan iklim usaha yang sehat. Pemerintah harus segera meninjau kembali kebijakan yang menimbulkan distorsi pasar dan memastikan bahwa keberpihakan terhadap BUMN tidak berarti mematikan kompetisi. Sebab, ekonomi yang kuat bukan hanya soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang memberi ruang keadilan untuk tumbuh bersama.
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
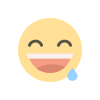 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
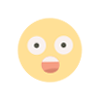 Wow
0
Wow
0































































