Pilkada Tidak Langsung: Antara Rasionalitas Politik dan Kemunduran Demokrasi
Wacana pilkada tidak langsung menjanjikan efisiensi, tetapi berisiko menggerus kedaulatan rakyat dan menguatkan oligarki jika sistem politik tak dibenahi.

Wacana pengembalian mekanisme pilkada tidak langsung kembali mengemuka di tengah kelelahan publik terhadap praktik demokrasi elektoral yang kian mahal, riuh, dan sarat problem. Pilkada langsung, yang sejak awal diposisikan sebagai instrumen pendalaman demokrasi lokal, justru dinilai gagal memenuhi janji dasarnya: melahirkan pemimpin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Biaya politik yang membengkak, politik uang yang semakin vulgar, hingga polarisasi sosial di akar rumput menjadi alasan utama munculnya gagasan bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya kembali diserahkan kepada DPRD. Namun, pertanyaannya bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal arah demokrasi itu sendiri.
Secara faktual, ongkos pilkada langsung memang tidak kecil. Setiap siklus pemilihan menguras anggaran negara dan daerah hingga triliunan rupiah. Belum lagi biaya yang harus ditanggung kandidat, yang kerap mendorong mereka mencari “balik modal” ketika berkuasa. Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung sering dipromosikan sebagai solusi rasional: lebih murah, lebih cepat, dan dianggap mampu meminimalkan konflik horizontal di masyarakat. Argumen ini terdengar masuk akal di atas kertas. Namun sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa rasionalitas prosedural tidak selalu sejalan dengan substansi demokrasi.
Pengalaman sebelum era pilkada langsung memperlihatkan bagaimana DPRD kerap menjadi arena transaksi elite. Pemilihan kepala daerah tidak jarang ditentukan oleh kompromi politik tertutup, lobi kekuasaan, dan kepentingan partai, bukan oleh aspirasi publik. Risiko ini tetap relevan hari ini, bahkan bisa semakin besar di tengah lemahnya institusionalisasi partai politik. Ketika partai lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral ketimbang institusi kaderisasi, menyerahkan sepenuhnya pilkada kepada DPRD berpotensi memperkuat oligarki lokal dan menjauhkan kepala daerah dari kontrol rakyat.
Di titik inilah dilema demokrasi muncul. Pilkada langsung memang tidak steril dari cacat, tetapi ia memberi ruang partisipasi dan legitimasi yang tidak bisa digantikan oleh mekanisme perwakilan semata. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki ikatan mandat dengan warga, setidaknya secara normatif lebih mudah dimintai pertanggungjawaban politik. Menghapus mekanisme ini berarti memutus satu jalur penting akuntabilitas publik, sekaligus mempersempit makna kedaulatan rakyat dalam demokrasi lokal.
Pendukung pilkada tidak langsung sering berargumen bahwa demokrasi tidak identik dengan pemilihan langsung. Secara teoritis, klaim ini benar. Banyak negara demokratis menerapkan mekanisme tidak langsung dalam berbagai level kekuasaan. Namun perbandingan tersebut kerap mengabaikan konteks. Demokrasi perwakilan hanya bekerja efektif ketika partai politik kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa prasyarat itu, pilkada tidak langsung berisiko menjadi demokrasi prosedural yang kehilangan roh.
Persoalan utama pilkada langsung sejatinya bukan terletak pada mekanismenya, melainkan pada ekosistem politik yang menyelubunginya. Regulasi pendanaan politik yang longgar, penegakan hukum pemilu yang inkonsisten, serta budaya politik transaksional menjadi akar masalah yang tak kunjung disentuh secara serius. Mengganti sistem pemilihan tanpa membenahi akar persoalan ibarat memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Karena itu, perdebatan pilkada tidak langsung seharusnya tidak disederhanakan menjadi pilihan hitam-putih antara menerima atau menolak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: demokrasi lokal seperti apa yang ingin dibangun? Jika tujuannya hanya efisiensi anggaran dan stabilitas jangka pendek, maka pilkada tidak langsung mungkin tampak menggoda. Namun jika demokrasi dipahami sebagai proses pendewasaan politik warga, partisipasi publik, dan kontrol terhadap kekuasaan, maka kemunduran mekanisme partisipatif justru berisiko membawa konsekuensi jangka panjang yang lebih mahal.
Pada akhirnya, demokrasi memang tidak pernah murah dan tidak selalu rapi. Ia menuntut kesabaran, pembenahan institusi, dan keberanian menghadapi ketidaksempurnaan. Pilkada langsung perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan. Reformasi pendanaan politik, penguatan partai, dan penegakan hukum yang tegas adalah pekerjaan rumah yang jauh lebih berat, tetapi juga lebih jujur. Menyerah pada pilkada tidak langsung tanpa prasyarat yang memadai berpotensi menjadi jalan pintas yang justru membawa demokrasi lokal mundur selangkah ke belakang.
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
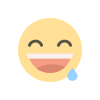 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
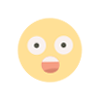 Wow
0
Wow
0



























































