Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Problem Struktural Tak Kunjung Usai
Penulis: Mursyidah Auni | Editor: Rein

KARTANEWS.COM, INDONESIA - Isu kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan di Indonesia bukan persoalan insidental. Dalam beberapa tahun terakhir, satuan pendidikan kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.
Fenomena ini memperlihatkan persoalan yang kian kompleks dari sekadar pelanggaran individu, melainkan menyangkut relasi kuasa, lemahnya sistem pencegahan, serta budaya diam yang masih mengakar.
Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan protektif, dalam sejumlah kasus justru menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan otoritas. Relasi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat hierarkis menciptakan ketimpangan kuasa.
Dalam situasi tertentu, ketimpangan ini membuka celah terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dominan dan anak perempuan sering menjadi kelompok paling rentan, meski anak laki-laki juga tidak luput dari risiko.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sektor pendidikan termasuk dalam klaster pengaduan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan melibatkan berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 (yang kini diperbarui dalam regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan) sebagai respons atas tingginya angka kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Regulasi ini lahir dari pengakuan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan bersifat sistemik dan kerap tidak tertangani dengan optimal.
Mengapa Lingkungan Pendidikan Rentan terhadap Kekerasan Seksual?
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pakar perlindungan anak menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor pendidikan kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual:
Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang
Guru atau pendidik memiliki otoritas akademik dan sosial atas peserta didik. Dalam kondisi tertentu, otoritas ini dapat disalahgunakan.
Budaya Hierarkis dan Kepatuhan Absolut
Dalam banyak praktik pendidikan, siswa diajarkan untuk patuh tanpa banyak bertanya. Pola ini berpotensi menghambat keberanian anak untuk menolak atau melaporkan tindakan tidak pantas yang dialaminya.
Minimnya Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif
Pendidikan tentang integritas tubuh, batasan pribadi (personal boundaries), dan hak anak atas perlindungan masih belum merata diterapkan. Topik seksualitas kerap dianggap tabu, sehingga anak tidak memiliki kosakata atau pemahaman untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan.
Stigma dan Ketakutan terhadap Reputasi Institusi
Dalam beberapa kasus, penyelesaian internal lebih diutamakan demi menjaga nama baik sekolah. Akibatnya, aspek pemidanaan atau keadilan bagi korban tidak selalu menjadi prioritas utama.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk tindakan yang merendahkan martabat seksual dan dilakukan dalam relasi kuasa dengan pemberatan hukuman apabila pelaku adalah pendidik.
Dengan kerangka hukum yang relatif komprehensif, tantangan utama kini terletak pada implementasi dan pengawasan.
Beberapa waktu lalu, dugaan kasus tindakan tidak pantas oleh seorang guru terhadap sejumlah siswa kelas V di Kabupaten Jember, Jawa Timur, viral dan menjadi perhatian dan peringatan serius bagi seluruh pihak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar martabat anak.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan di Jember. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh, bukan tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar hak atas integritas tubuh anak. Apa pun alasannya, tindakan meminta anak menanggalkan pakaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Berdasarkan koordinasi KemenPPPA dengan UPTD PPA Kabupaten Jember, dari 22 siswa di kelas tersebut, terdapat enam anak yang berada di dalam kelas dan diduga mengalami perlakuan tidak pantas. Peristiwa bermula dari tuduhan kehilangan uang yang berujung pada tindakan memerintahkan siswa menanggalkan pakaian.
Menteri PPPA menegaskan bahwa tindakannya berpotensi melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Selain itu, jika terdapat unsur yang menyerang kehormatan atau kesusilaan berdasarkan seksualitas anak, maka dapat dikaitkan dengan UU TPKS dengan pemberatan apabila dilakukan oleh pendidik.
Kasus di Jember menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi normatif tapi diperlukan langkah sistemik, antara lain:
- Penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah
- Pendidikan integritas tubuh dan hak anak sejak dini
- Mekanisme pengaduan yang aman dan Independen
- Transparansi dan koordinasi lintas sektor
- Penegakan ukum tanpa kompromi
Pada akhirnya, persoalan kekerasan seksual di sektor pendidikan bukan semata persoalan moral individu, melainkan ujian komitmen negara dalam melindungi hak anak. Tanpa reformasi sistem pengawasan dan perubahan budaya institusional, risiko kekerasan seksual akan berulang terus dan membayangi ruang-ruang pendidikan generasi Indonesia.
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
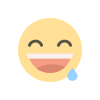 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
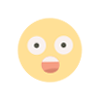 Wow
0
Wow
0





































































