Kebijakan Publik: Sah secara Politik, Rapuh secara Sosial
Kebijakan publik kerap sah secara politik, namun rapuh secara sosial. Tanpa partisipasi bermakna dan kebijakan berbasis data, demokrasi berisiko menjadi prosedur kosong.

Dalam negara demokrasi, kebijakan publik kerap diklaim sebagai wujud kehendak rakyat, tetapi realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Banyak kebijakan lahir melalui prosedur yang sah dibahas di parlemen, disahkan lewat regulasi, dan diumumkan secara resmi namun gagal menjawab persoalan mendasar masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, menampilkan wajah demokrasi prosedural yang lengkap, tetapi menyisakan polemik berkepanjangan karena minimnya partisipasi publik yang bermakna dan lemahnya komunikasi kebijakan. Gelombang penolakan dari buruh, akademisi, hingga masyarakat sipil menunjukkan bahwa legalitas formal tidak otomatis berbanding lurus dengan legitimasi sosial.
Fenomena serupa tampak dalam berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur. Di sejumlah daerah, proyek strategis nasional berjalan cepat atas nama pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan kesiapan sosial dan dampak lingkungan. Kasus relokasi warga akibat pembangunan bendungan atau kawasan industri kerap memperlihatkan ketimpangan relasi antara negara dan warga. Ganti rugi yang tidak sebanding, proses konsultasi yang terbatas, hingga hilangnya mata pencaharian lokal mempertegas bahwa kebijakan publik sering kali lebih berpihak pada target proyek daripada keberlanjutan hidup masyarakat terdampak.
Dalam sektor perlindungan sosial, kebijakan bantuan sosial juga menghadapi persoalan serupa. Program bantuan tunai yang dirancang untuk meredam dampak krisis ekonomi tidak jarang tersandung masalah data. Banyak warga miskin tercecer karena tidak tercatat, sementara penerima yang relatif mampu justru masih mendapatkan bantuan. Persoalan data terpadu kesejahteraan sosial yang berulang ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis angka tanpa verifikasi lapangan berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Negara hadir, tetapi tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Kebijakan pendidikan pun tak luput dari kritik. Penerapan sistem zonasi sekolah, misalnya, digagas dengan tujuan mulia untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasinya di banyak daerah menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur dan kualitas sekolah yang belum merata. Alih-alih mengurangi kesenjangan, kebijakan ini justru memicu keresahan orang tua dan praktik manipulasi alamat. Lagi-lagi, kebijakan yang baik secara konsep terjebak pada pelaksanaan yang abai terhadap konteks sosial.
Contoh-contoh tersebut memperlihatkan pola yang sama: kebijakan publik dirumuskan dengan logika administratif dan politik, tetapi kurang diuji melalui dialog sosial yang jujur. Partisipasi publik sering dipersempit menjadi formalitas konsultasi, bukan ruang deliberasi yang setara. Kritik dianggap gangguan, bukan sumber koreksi. Akibatnya, kebijakan kehilangan daya ikat sosial dan berumur pendek karena terus dipersoalkan.
Membingkai ulang kebijakan publik menjadi keharusan jika demokrasi tidak ingin terjebak sebagai prosedur kosong. Kebijakan harus kembali diposisikan sebagai alat pemecahan masalah publik, bukan sekadar pencapaian politik atau target pembangunan. Demokrasi diuji bukan saat kebijakan disahkan, melainkan ketika ia dijalankan dan dirasakan adil oleh warganya. Tanpa koreksi serius, kebijakan publik akan terus sah secara politik, tetapi rapuh secara sosial—dan demokrasi pun perlahan kehilangan maknanya.
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
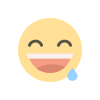 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
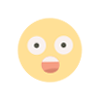 Wow
0
Wow
0





























































